Thursday, September 16, 2010
Menempa Jati Diri Bangsa
 Kata Pengantar:
Kata Pengantar:Susilo Bambang Yudhoyono
Menko Polkam Republik Indonesia, dalam buku Nasionalis Religius, Jati diri bangsa
Karakter setiap bangsa berbeda-beda, tetapi diantara perbedaan itu ada karakter universal yang bisa dijadikan entry point pembentukan karakter kebangsaan. Memang manusia itu mewarisi kualitas genetika orang tua, kualitas sosial dan kualitas kebangsaan.
Akan tetapi manusia juga adalah makhluk yang tidak tunduk begitu saja kepada lingkungan. Ia bisa berfikir, menganalisa dan mendistorsi lingkungan sesuai dengan kapasitas berfikirnya. Identitas manusia tidak hanya sebagai individu, tetapi ia juga memiliki identitas keluarga, identitas kelompok, identitas etnik dan identitas bangsa. Dalam lingkungan yang sempit manusia cenderung menggunakan identitas yang sempit pula, yaitu identitas pribadi dan identitas keluarga. Dalam lingkungan yang luas, identitas individual dapat terdistorsi oleh identitas yang lebih besar sesuai dengan lingkungannya. Ketika seseorang dalam perantauan domestik, maka identitas kampung halaman lebih dominan dibanding identitas individu dan identitas keluarga. Tetapi ketika seseorang berada di luar negeri maka yang dominan pada orang itu adalah identitas kebangsan.
Dalam perspektif diatas, maka jika membangun kualitas keluarga dimulai dari membangun individu, membangun suatu bangsa tidak dengan berangkat dari membangun individu-individu, tetapi harus membawa bangsa itu ke tengah lingkungan international, membawa bangsa itu dalam pergaulan antar bangsa agar yang terbangun bukan hanya konsep diri individual tetapi juga konsep diri kebangsaan. Dalam pergaulan antar bangsa, identitas kebangsaan akan tumbuh subur. Dalam percaturan international warga bangsa akan dapat bercermin kepada bangsa lain, sehingga pusat perhatiannya terpusat pada bagaimana membesarkan bangsa menjadi kekuatan yang diperhitungkan oleh bangsa lain. Ukuran kebesaran bangsa bisa diukur pada supremasi militernya, bisa juga dalam hal dominasi ekonomi , dan bisa juga pada ketinggian kebudayaannya. Ketinggian kebudayaan suatu bangsa akan mengantar pada supremasi yang lain. Dengan kata lain membangun karakter bangsa adalah dengan membudayakan nilai akhlak dalam kehidupan bangsa, artinya nilai-nilai moral dan akhlak harus masuk ke dalam sistem berbangsa dan bernegara, dalam perundang-undangan yang mengikat.
Sebagai contoh, kejujuran seseorang bersumber dari hatinya. Membudayakan kejujuran kepada bangsa bukan dengan menyerahkan kepada hati masing-masing warga negara, melainkan melalui sistem transparansi dan sistem pengawasan dimana peluang untuk tidak jujur menjadi semakin sempit. Setiap warga negara, terutama para penyelenggara negara haruslah terakses kekayaannya oleh sistem pengawasan. Sistem tersebut mengharuskan setiap warga negara memiliki file yang merekam setiap transaksi, dan setiap saat mereka harus bisa membuktikan asal usul harta kekayaanya secara sistemik dan terbuka. Sistem file dan transparansi tersebut akan memperkecil ruang gerak orang yang bertindak tidak jujur dalam aktifitas ekonomi. Sistem itu juga harus mencakup sanksi terhadap ketidak jujuran warga yang juga dilaksanakan secara terbuka.
Meski boleh jadi seseorang mematuhi peraturan itu belum tentu dilandasi oleh niat ibadah, tetapi sistem yang berjalan lama akan membentuk perilaku masyarakat, membentuk karakter dan jati diri bangsa.
Membangun jati diri bangsa bukanlah pekerjaan mudah, oleh karena itu harus bersistem, melibatkan banyak elemen masyarakat. Para agamawan secara mikro harus aktif mengingatkan masyarakat untuk mematuhi peraturan dan menghubungkan etos kepatuhan itu dengan niat ibadah. Secara makro harus ada kelompok yang secara terus menerus mengingatkan kepada para pemimpin bangsa dan penyelenggara negara untuk menjadi contoh dalam hal kepatuhannya kepada peraturan, termasuk pemberlakuan sanksi jika ada pemimpin yang melanggar peraturan.
Karakteristik tiap bangsa berbeda-beda, dan efektifitas sistem juga berbeda-beda. Pada bangsa yang tingkat pendidikanya tinggi maka demokratisasi, kebebasan dan keterbukaan sangat efektif dalam membangun karakter dari bangsa itu, tetapi pada bangsa yang tradisionil dan tingkat pendidikan warganya tidak merata maka keteladanan seorang pemimpin lebih efektif dibanding demokratisasi dan keterbukaan. Pada bangsa kita, demokrasi tidak bisa dilempar ke pasar bebas tanpa memperhatikan nilai-nilai budaya lokal.
Manusia Indonesia, Sebuah Cermin
Di waktu yang lalu, banyak diantara kita orang Indonesia yang dengan bangga menyebut kepribadian orang Indonesia yang ramah, santun dan toleran dan bahkan religius. Atribut itu bukan hanya dipromosikan oleh Departemen Penerangan dan Departemen Luar Negeri, tetapi sebagian besar kita seperti membenarkan pernyataan itu. Gelombang reformasi menjelang Milenium ketiga memporak-porandakan semua citra itu. Peristiwa yang terjadi selama kurun reformasi seperti penjarahan massal atas milik orang lain, tindakan main hakim sendiri secara amat sadis kepada pelaku kriminal, fatsoen politik anggauta parlemen (dan demonstran) yang sangat vulgar, amuk massa dan pembakaran rumah-rumah penduduk, pembunuhan massal dan sadis dalam konflik antar etnik mencerminkan watak dari manusia yang tidak ramah, tidak santun dan tidak menghargai hak azazi manusia, dan tidak juga mencerminkan masyarakat beragama. Memang masih dipertanyakan, apakah fenomena ini sekedar eforia reformasi atau justeru merupakan jati diri asli bangsa Indonesia.
Bangsa Indonesia juga dikenal sebagai bangsa yang memiliki tingkat paternalisme yang tinggi dimana rakyat mempunyai hubungan yang sangat emosionil dengan pemimpinnya. Dari segi pembentukan karakter bangsa (nation building), sifat paternalis bangsa bisa dipandang sebagai aset positif, yakni perilaku bangsa akan sangat mudah dibentuk manakala para pemimpinnya mampu menjadi contoh yang baik bagi rakyatnya. Kekuatan keteladanan pemimpin bagi rakyat paternalis itu sangat tinggi efektifitasnya dibanding sistem administrasi. Oleh karena itu pada kasus bangsa Indonesia, membangun jati diri bangsa harus dipusatkan pada mengawasi dan menjaga moralitas pemimpin. Pelanggaran nilai moral dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pemimpin sama sekali tidak boleh ditolerir. Penegakan hukum dan sanksi moral kepada elit pemimpin harus menjadi prioritas utama dari penegakan sistem tersebut. Dengan itu maka rakyat di bawahnya yang paternalis itu secara psikologis akan mematuhi nilai-nilai hukum dan nilai-nilai kepatutan. Sistem keteladanan ini akan sangat kecil biayanya dibanding biaya menyediakan infrastruktur pengawasan secara nasional.
Apa yang disebutkan diatas, baru sebatas gagasan. Ketika gagasan itu akan diterapkan di Indonesia, timbul pertanyaan, mana yang harus dilaksanakan lebih dahulu, mengingat problem kehancuran moral bangsa dewasa ini sudah sangat kompleks. Idealnya pembangunan jati diri bangsa itu melalui sistem pendidikan dan dimulai dari anak-anak dan generasi muda. Akan tetapi, disamping membutuhkan waktu yang panjang, kompleksitas moral masyarakat akan dapat menghilangkan makna pendidikan generasi muda karena pasca pendidikan, mereka akan dengan mudah terkontaminasi oleh keadaan masyarakat yang bertentangan dengan nilai-nilai yang diajarkan kepada mereka. Di kalangan komunitas pendidikan, meski terlambat, sudah tumbuh kesadaran bahwa sistem pendidikan nasional yang diberlakukan selama ini gagal melahirkan anak didik yang sanggup berkompetisi di dunia global, bahkan juga gagal melahirkan anak didik yang mampu memahami potensi daerahnya, karena selama satu generasi sistem pendidikan nasional kita lebih menekankan keseragaman. Problem pendidikan dewasa ini menyerupai telor dan ayam, mana yang harus didahulukan. Oleh karena itu diperlukan adanya pemikiran kreatif dan bersifat alternatif dalam pendidikan yang komprehensip, serentak, menyangkut seluruh lapisan masyarakat. Meskipun tingkat kerusakan moral masyarakat sifatnya menyeluruh, tetapi pasti ada kata kunci untuk mengurai problem tersebut.
Nasionalisme, Pluralisme dan Humanisme
Dalam era global dimana dunia menjadi kampung besar dan informasi global tidak bisa dihalangi memasuki rumah-rumah penduduk, maka disamping bangsa harus ditempa dengan nilai-nilai luhur budaya sendiri, juga harus disiapkan menghadapi laju perubahan yang tak bisa dihindar, yaitu arus globalisasi. Ada tiga kata kunci untuk mempersiapkan jati diri bangsa menghadapi serbuan budaya global, yaitu; (1) memperkokoh semangat nasionalisme, yaitu betapapun bangsa Indonesia harus memahami dan mengedepankan identitas nasionalnya sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai luhur budaya dan moralitas agama. Bangsa yang kehilangan jati diri nasionalnya akan tidak memiliki bargaining position dalam pergaulan antar bangsa. (2) Memelihara semangat pluralis. Bahwa bangsa Indonesia memang terdiri dari berbagai suku, budaya dan agama, tetapi keragaman itu dikelola sedemikian rupa sehingga menjadi kekayaan, menjadi potensi, bukan menjadi penghalang. Semangat pluralis akan dapat menjadi filter ketika berjumpa dengan budaya bangsa lain, yakni tetap berbangga dengan budaya bangsa sendiri yang luhur, dan hanya mengadopsi budaya lain yang telah teruji memiliki nilai lebih baik. (3) Humanisme, yakni bahwa bangsa Indonesia harus bisa menghormati harkat manusia seperti yang diajarkan oleh agama, yakni insan sebagai makhluk psikologis, sebagai makhluk budaya, sebagai makhluk sosial, sebagai hamba Allah dan sebagai khalifatullah. Sebagai makhluk yang bermartabat, manusia harus dilindungi hak-hak azazinya, jiwanya, intelektualitasnya, keyakinan agamanya, kepemilikannya dan kesucian identitas dirinya.
Mengakhiri tulisan ini sebagai pengantar buku kecil karya DR. Achmad Mubarok, MA, yang berjudul Nasionalis Religius Jati diri Bangsa Indonesia, saya sangat mengapresiasi tulisan tersebut, bukan saja dari tulisannya, tetapi dari penulisnya. Saya mengenal penulis sebagai ilmuwan dan ulama yang dari pengalaman panjang hidupnya kemudian memiliki sosok nasionalis religius. Insya Allah buku ini banyak manfaatnya bagi bangsa.
Jakarta, 9 Januari 2004
Susilo Bambang Yudhoyono




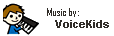
Post a Comment