Tuesday, December 14, 2010
Militansi Minoritas
 Mayoritas bisa bermakna jumlah, juga bisa bermakna kualitas. Ummat Islam adalah mayoritas di negeri Indonesia, tetapi belum menjadi mayoritas dalam arti kualitas. Jumlah orang pandai dan orang kaya dari ummat Islam Indonesia sangat kecil prosentasinya, sementara orang Kristen itu minoritas dalam jumlah tetapi mayoritas dalam kualitas.
Mayoritas bisa bermakna jumlah, juga bisa bermakna kualitas. Ummat Islam adalah mayoritas di negeri Indonesia, tetapi belum menjadi mayoritas dalam arti kualitas. Jumlah orang pandai dan orang kaya dari ummat Islam Indonesia sangat kecil prosentasinya, sementara orang Kristen itu minoritas dalam jumlah tetapi mayoritas dalam kualitas.Pada era Pak Harto misalnya pernah semua jabatan strategis diduduki oleh orang Kristen. Bidang hankam ada Jenderal Pangabean dan Jendral Beni Murdani, bidang ekonomi keuangan ada Sumarlin dan Fran Seda, dan bidang birokrasi, ketua BAKN pun dijabat oleh orang Kristen, luar biasa, dalam kurun waktu yang sama, wilayah-wilayah strategis dipegang oleh orang Kristen. Mengapa, karena minoritas itu biasanya militant. Baru setelah era demokrasi terbuka, ummat Islam sebagai mayoritas bisa menduduki kursi-kursi strategis.
NTT dan Irian atau Papua itu wilayah minoritas bagi ummat Islam. Ummat Islam di dua wilayah itu mengalami serba ketinggalan, ekonomi, pendidikan dan politik. Jika dana program humanitarian Vatican (dan dana asing lainnya) mudah masuk NTT dan Papua, orang Islam di sana sangat sulit akses dana pendidikan yang bersumber dari luar negeri. Tetapi jiwa militant yang disemangati karena keminoritasannya menutupi kekurangan itu. Banyak sekali mahasiswa dan pelajar asal Papua dan NTT yang dengan segala kekurangan finasialnya berjuang mati-matian menutut ilmu di kota-kota besar Jawa, Jakarta, Yogya, malang dan Surabaya.
Mereka memiliki obsesi bukan saja ingin sukses studi dan bekerja demi kampung halamannya, tetapi juga merasa terpanggil untuk menjadi da`i untuk meningkatakan kualitas keislaman masyarakatnya yang minoritas itu. Dari Papua yang belajar di Pesantren Assyafi`iyyah Jakarta misalnya, sekarang di Papua mereka berhasil mendirikan Pesantren, juga dengan nama Pesantren Assyafi`iyyah.
Dari NTT lain lagi kerjanya. Mereka suka membawa anak-anak miskin dari kampungnya ke Jakarta untuk bisa sekolah atau kuliah. Yang mengagumkan mereka orang miskin, tetapi semangat mencari donator untuk teman-temannya tak kenal lelah. Mereka juga mendirikan organisasi Ikatan Pemuda dan Mahasiswa Timor (IPMAT) Dikit-dikit sayapun terkadang dimintai bantuan, untuk biaya transit terutama. Mereka menaroh anak-anak kampong itu di Pesantren Yatim atau di asrama yang dibiayai donator. Sebagian bahkan sudah bisa masuk perguruan tinggi, dan obsesi mereka nanti bisa pulang kampong membangun negeri.
Belum lama ini saya membaca ada 11 remaja asal Amanuban Timur yang dihebohkan menjadi korban traficking anak-anak. Bupati, Wk.Ketua DPRD dan Polisi turun tangan. Sesungguhnya menengarai praktek traficking anak-anak itu sangat mudah, dan 11 anak yang dihebohkan itu jelas bukan korban trafiking, tetapi lebih sebagai “korban” militansi minoritas. Banyak mahasiswa asal NTT yang dulu prosesnya juga seperti itu, dibawa oleh ekponen NTT, ditampung, dicarikan donator dan akhirnya bisa kuliah. Karena modal pas-pasan mereka sering tidak melengkapi persyaratan, misalnya surat jalan atau identitas yang diperlukan.
Sesungguhnya yang mungkin merasa terganggu adalah saudara-saudara dari gereja, karena militansi mereka akhirnya harus jadi rival dalam penyiaran agama. Hal ini Nampak dari pernyataan Ketua Sinode GMIT, Pdt, Dr. Eben Nuban Timo yang begitu semangat melakukan kriminalisasi terhadap kasus itu. Nampaknya kepolisian NTT juga menjadi serba salah, menganggap sebagai traficking anak-anak seperti yang dikatakan oleh Bupati TTS Paul Mella dan wakil Ketua DPRDTTS, atau sekedar “korban” militansi minoritas. Mungkin sebagian anak-anak yang dibawa ke Jakarta masuk kategori mualaf Sehingga mengusik kemapanan gereja.




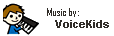
Kasus itu memang sengaja dibesar-besarkan oleh awak media yang ditunggangi oleh kepentingan beberapa oknum yang sengaja untuk menghancurkan perkembangan Islam di pedalaman Timor.
Kasus itu imbas dari ketidak pedulian PEMDA terhadap akses pendidikan yang layak bagi minoritas Muslim yang ada di Timor, jadi mereka berinisiatif untuk menyekolahkan adik2nya dengan berbagai cara.
Tuduhan untuk dipekerjakan sebetulnya adalah salah alamat karena yang ada justru mendapatkan donatur atau orang tua asuh agar nasib mereka dapat terperhatikan dengan betul.
Lihat saja yang jadi preman di Jakarta asal Timor dari kelompok mana? Muslim atau Non Muslim?
Post a Comment